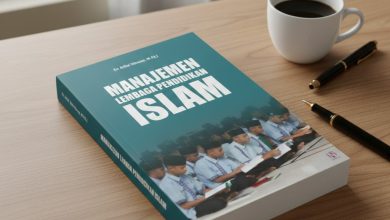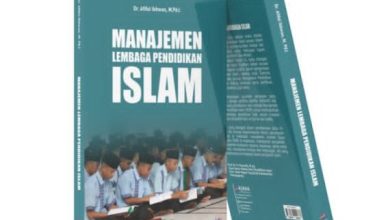Antara Kader Muhammadiyah dan Kader Partai: Sebuah Refleksi Identitas
Penulis: Darmanto Saputro || Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Ponorogo
Saya pernah bersekolah di SMA Muhammadiyah hingga akhirnya melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah. Namun, di lingkungan tempat saya tinggal, pernah suatu ketika saya menghadiri undangan tahlilan seorang tetangga. Di sana, dengan suara sayup, seseorang berbisik, “Itu lho, kader Muhammadiyah.”
Saya pun penasaran. Pada kesempatan lain, saya bertanya kepada seorang sahabat, “Dari mana kamu tahu saya kader Muhammadiyah? Karena saya tidak pernah menunjukkan bahwa saya aktif di organisasi otonom Muhammadiyah.” Jawabannya sederhana, “Cara kamu bicara dan berpikir condong ke Muhammadiyah.” Yang menarik, dalam hati saya justru merasa nyaman dan bangga disebut demikian. Padahal, saya biasa saja serta membaur dengan yang lain. Sebutan “kader Muhammadiyah” itu terasa seperti sebuah pengakuan atas nilai-nilai yang saya anut.
Pengalaman kecil ini mengungkap sebuah fenomena: di mata masyarakat, label “kader Muhammadiyah” sangatlah cair dan inklusif. Orang tidak pernah memeriksa kartu anggota atau struktur kepengurusan. Mereka melihat dari cara bicara, pola pikir, atau praktik keagamaan seseorang. Tidak ikut tahlilan atau tidak memakai qunut dalam salat Subuh? Itu sudah cukup bagi sebagian orang untuk menyematkan label “Muhammadiyah.”
Bahkan, tokoh seperti Soekarno yang pernah mengajar di sekolah Muhammadiyah di Bengkulu atau Soeharto yang bersekolah di SMP Muhammadiyah kerap disebut sebagai “kader.” Seorang teman saya yang secara kultural merupakan penganut Islam kejawen pun dengan bangga menyebut dirinya alumni kampus Muhammadiyah. Inilah kekuatan identitas kultural Muhammadiyah: ia melekat sebagai nilai, pendidikan, dan cara pandang, bukan sekadar keanggotaan formal.
Namun, dalam internal organisasi, sebutan “kader” justru lebih spesifik dan tidak terlalu menonjol di ruang publik. Ia umumnya terkait dengan proses pengkaderan formal. Belakangan, istilah “kader Muhammadiyah” ramai diperbincangkan di media, terutama ketika muncul nama-nama yang disebut sebagai “kader” lalu diangkat menjadi menteri. Di sinilah kerancuan dan batasan perlu diperjelas.
Muhammadiyah adalah organisasi sosial-keagamaan, bukan organisasi politik. Sebagai organisasi, Muhammadiyah bersikap netral dan tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun. Aturannya tegas: simbol, atribut, nama, dan segala fasilitas organisasi dilarang digunakan untuk kepentingan politik praktis, termasuk kampanye. Setiap warga Muhammadiyah yang ingin terjun ke politik diberi kebebasan, tetapi itu murni hak politik pribadi, bukan representasi organisasi. Pesannya jelas: “Silakan berkiprah di partai mana pun, tapi jaga nama baik Muhammadiyah. Jangan mempermalukan organisasi.”
Oleh karena itu, ketika seorang warga Muhammadiyah berprestasi di partai politik dan kemudian diusulkan menjadi menteri, logika pertanggungjawabannya harus lurus. Ia diangkat sebagai kader atau utusan partainya, bukan sebagai utusan Muhammadiyah. Tanggung jawab formalnya adalah kepada Presiden yang mengangkatnya dan kepada partai politik yang mengusulkannya, bukan kepada Muhammadiyah.
Muhammadiyah juga tidak pernah meminta pertanggungjawaban politik para kadernya yang menjadi pejabat. Prestasi atau permasalahan yang ia buat dalam jabatan politik merupakan urusan pribadi dan partainya.
- Inilah garis pemisah yang penting: Kader Muhammadiyah dan kader partai politik berada di ranah yang berbeda.
Kader Muhammadiyah adalah identitas kultural dan keagamaan yang melekat pada individu karena nilai, pendidikan, atau afiliasi keluarganya. Ia berbasis pada komitmen moral dan intelektual untuk memperjuangkan kemajuan umat sesuai khittah organisasi. - Kader Partai Politik adalah identitas dan posisi politik formal dalam struktur kekuasaan. Ia memiliki garis komando, tanggung jawab, dan loyalitas kepada institusi politik tempatnya bernaung.
Seorang menteri bisa saja menyandang kedua identitas ini secara bersamaan, tetapi pada level yang berbeda. Secara personal, ia adalah seorang Muslim yang dibesarkan oleh nilai-nilai Muhammadiyah. Secara institusional, ia adalah pejabat negara yang bertanggung jawab atas kebijakannya kepada Presiden dan partai pengusungnya.
Kesimpulannya, publik perlu bijak membedakan. Jangan mencampuradukkan antara identitas kultural seseorang dengan tanggung jawab formal atas jabatan politiknya. Muhammadiyah, sebagai organisasi, telah dengan tegas menjaga khittahnya: mendidik kader untuk berakhlak dan berkontribusi bagi bangsa tanpa terjebak dalam pusaran politik praktis. Sementara itu, warganya yang menjadi pejabat publik harus profesional dan bertanggung jawab penuh pada jalur politik yang telah mereka pilih.
Dengan pemahaman ini, kita dapat menghargai kontribusi setiap anak bangsa tanpa mengaburkan mandat dan posisi masing-masing institusi.